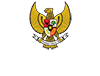Prof. Dr. Achmad Kholik, M.Ag (Guru Besar Hukum Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)
Menggali Potensi Zakat Sebagai Solusi Fiskal
25/09/2025 | Humas BAZNAS MinahasaOleh : Prof. Dr. Achmad Kholik, M.Ag (Guru Besar Hukum Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. MK menilai permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.Putusan yang dibacakan pada Kamis (28/8/2025) di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK itu, menegaskan kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga utama pengelola zakat di Indonesia. Putusan ini turut mendorong upaya menggali potensi zakat sebagai solusi fiskal di Indonesia.
Dalam sistem ekonomi modern, pajak merupakan salah satu instrumen utama untuk menopang pembiayaan negara. Namun, bagi umat Islam, keberadaan zakat sebagai kewajiban syar’i seringkali menimbulkan pertanyaan ketika harus membayar pajak dan zakat secara bersamaan.
Fenomena ini tidak hanya membebani individu, tetapi juga menimbulkan perdebatan tentang keadilan fiskal dalam masyarakat Muslim. Zakat bukan sekadar ritual ibadah, melainkan memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat kuat, termasuk dalam mengurangi kesenjangan dan mendukung distribusi kekayaan yang adil. Di sinilah pentingnya membahas zakat sebagai instrumen fiskal alternatif yang dapat bersinergi dengan kebijakan pajak negara.
Konsep Zakat dalam Islam dan Tujuan Fiskal Negara
Konsep zakat dalam Islam memiliki fungsi yang sejalan dengan tujuan fiskal negara, yaitu mengumpulkan dana untuk kepentingan publik, memberantas kemiskinan, dan mewujudkan keadilan sosial. Bedanya, zakat memiliki legitimasi agama yang kuat dan disalurkan kepada delapan golongan penerima yang telah diatur dalam Alquran.
Jika diintegrasikan secara tepat dalam sistem keuangan negara, zakat dapat menjadi sumber dana yang signifikan dan berkontribusi dalam mengurangi beban pajak bagi umat Islam. Beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi telah mengadopsi model ini, di mana zakat yang dibayar dapat mengurangi kewajiban pajak, sehingga tidak ada dobel pembayaran yang membebani umat.
Meskipun gagasan zakat sebagai instrumen fiskal memiliki potensi besar, implementasinya tidak lepas dari tantangan, terutama terkait harmonisasi regulasi antara hukum negara dan syariat Islam. Dibutuhkan regulasi yang jelas, sistem pengelolaan yang transparan, serta sinergi antara lembaga zakat dan otoritas pajak agar integrasi ini berjalan efektif.
Jika hal ini terwujud, zakat tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga instrumen ekonomi strategis yang mampu memperkuat fiskal negara dan memberikan keadilan bagi umat Islam. Dengan demikian, integrasi zakat dan pajak bukan sekadar wacana, melainkan solusi konkret bagi ekonomi berkeadilan.
Solusi Fiskal
Potensi zakat di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, seiring dengan jumlah penduduk Muslim yang dominan. Berdasarkan hasil riset BAZNAS dan lembaga-lembaga independen, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp 300–327 triliun per tahun.
Namun, capaian realisasi pengumpulan zakat masih sangat jauh dari angka potensial tersebut, yakni hanya sekitar Rp 20–30 triliun per tahun. Angka ini kurang dari 15% dari potensi yang ada.
Rendahnya realisasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih menghadapi tantangan serius dalam aspek literasi, kesadaran muzaki, dan optimalisasi teknologi digital untuk penghimpunan dan distribusi. Padahal, jika potensi zakat ini dapat dimaksimalkan, ia berpeluang besar menjadi sumber daya ekonomi alternatif yang strategis, baik untuk pengentasan kemiskinan maupun sebagai instrumen kebijakan fiskal nasional.
Manfaat Zakat sebagai Instrumen Fiskal
Manfaat zakat sebagai instrumen fiskal tidak dapat diabaikan. Pertama, zakat mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial secara signifikan jika dikelola dengan prinsip manajemen modern dan distribusi yang tepat sasaran. Zakat bersifat spesifik karena penerimanya sudah ditentukan syariat (delapan asnaf), yang sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi lemah.
Dengan pengelolaan terstruktur, zakat dapat menjadi stimulus pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar bantuan konsumtif. Kedua, zakat dapat mengurangi beban ganda umat Islam, yang selama ini harus menanggung kewajiban pajak negara sekaligus kewajiban zakat agama.
Jika zakat diakui secara resmi dalam sistem fiskal, setidaknya melalui pengurangan pajak yang lebih proporsional, maka beban finansial umat Muslim akan lebih ringan tanpa mengurangi penerimaan negara secara drastis. Ketiga, integrasi zakat dalam kebijakan fiskal dapat memperkuat penerimaan negara berbasis nilai-nilai syariah. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang mengakomodasi keberagaman sistem nilai, serta mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang etis dan berorientasi keadilan sosial.
Namun, pertanyaannya adalah bagaimana skema integrasi zakat dan pajak dapat diterapkan? Saat ini, skema yang berlaku di Indonesia adalah zakat sebagai pengurang pajak (tax deduction). Artinya, jumlah zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ resmi dapat mengurangi penghasilan kena pajak seseorang.
Skema ini relatif aman dan tidak menimbulkan gangguan terhadap penerimaan negara, tetapi dampaknya terhadap beban ganda umat Islam masih terbatas. Alternatif kedua yang lebih radikal adalah zakat sebagai pengganti pajak (tax substitution), yakni zakat menggantikan sebagian atau seluruh kewajiban pajak bagi umat Islam. Secara teori, skema ini menarik karena dapat menghilangkan beban ganda dan menciptakan rasa keadilan bagi Muslim taat yang menunaikan zakat.
Namun, penerapan skema ini menghadapi sejumlah tantangan besar. Dari sisi pro, tax substitution dapat meningkatkan kepatuhan zakat, memperkuat peran lembaga zakat, dan mengurangi resistensi masyarakat terhadap pajak.
Akan tetapi, dari sisi kontra, langkah ini berpotensi menimbulkan defisit fiskal yang besar karena potensi penerimaan pajak jauh lebih tinggi daripada realisasi zakat saat ini. Selain itu, isu keadilan fiskal akan mengemuka, mengingat Indonesia adalah negara multireligius yang harus menjamin kesetaraan kewajiban warga negara.
Untuk menjembatani pro dan kontra tersebut, pendekatan yang paling realistis adalah memperkuat skema tax deduction secara lebih efektif, misalnya dengan memberikan pengurangan pajak yang lebih signifikan bagi muzaki yang membayar zakat melalui lembaga resmi, serta memperketat integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak dan BAZNAS.
Di sisi lain, perlu strategi masif untuk meningkatkan literasi zakat, memperluas kanal pembayaran digital, serta mendorong inovasi distribusi zakat berbasis pemberdayaan ekonomi produktif.
Jika optimalisasi ini berhasil, maka wacana tax substitution mungkin dapat dipertimbangkan secara bertahap di masa depan, misalnya untuk sektor atau golongan tertentu, dengan mempertimbangkan stabilitas fiskal negara dan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun kesejahteraan nasional yang berkeadilan.
Zakat dan Instrumen Fiskal
Zakat dalam Islam merupakan pilar penting yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi. Secara etimologis, zakat bermakna tumbuh dan suci, menunjukkan fungsinya untuk membersihkan harta dan menumbuhkan keberkahan.
Lebih jauh, zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan agar tidak terpusat, sebagaimana ditegaskan dalam QS At-Taubah ayat 60 tentang delapan golongan penerima. Dengan demikian, zakat tidak sekadar ibadah ritual, tetapi instrumen pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial.
Instrumen fiskal, di sisi lain, adalah kebijakan negara untuk mengatur perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran, dengan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Pajak berfungsi bukan hanya menghimpun dana, tetapi juga mengatur stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan pembangunan nasional. Berbeda dengan zakat yang bersifat religius dan diwajibkan bagi Muslim tertentu, pajak bersifat legal formal dan berlaku universal bagi seluruh warga negara.
Meskipun berbeda dari segi dasar hukum dan sasaran, zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama: kesejahteraan masyarakat. Hal ini memunculkan wacana integrasi zakat sebagai bagian dari instrumen fiskal di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, yang potensinya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Namun, implementasi integrasi ini menuntut regulasi yang jelas, transparansi, serta harmonisasi antara prinsip syariah dan sistem perpajakan agar tercipta keadilan tanpa memberatkan umat.
Realitas dan Tantangan
Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memiliki potensi zakat yang sangat besar. Regulasi pengelolaan zakat telah diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011, yang menegaskan peran BAZNAS dan LAZ dalam pengumpulan dan distribusi zakat secara akuntabel.
Pemerintah juga memberikan insentif melalui mekanisme tax deduction, di mana zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, kebijakan ini belum sampai pada tahap tax substitution karena pajak masih menjadi tulang punggung APBN.
Implementasi integrasi zakat dan pajak menghadapi sejumlah kendala. Pertama, keterbatasan integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak dan BAZNAS menghambat verifikasi zakat sebagai pengurang pajak.
Kedua, wacana zakat menggantikan pajak menimbulkan isu keadilan dalam negara multireligius. Ketiga, dari sisi fiskal, pajak menyumbang lebih dari 70% penerimaan APBN, sedangkan realisasi zakat baru sekitar 10–15% dari potensi Rp 327 triliun per tahun.
Tantangan lain adalah rendahnya literasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi. Sebagian besar muzaki masih menyalurkan zakat secara langsung sehingga tidak tercatat dalam sistem negara.
Dengan demikian, integrasi zakat sebagai instrumen fiskal masih terbatas pada kebijakan parsial. Untuk memperkuat peran zakat, diperlukan sinergi regulasi, penguatan teknologi administrasi, dan edukasi publik agar zakat mampu mendukung kesejahteraan nasional tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Meskipun wacana zakat sebagai instrumen fiskal menarik secara teoretis, pengganti pajak sepenuhnya dinilai tidak realistis dalam jangka pendek. Alasannya, struktur APBN sangat bergantung pada pajak, sementara tingkat kepatuhan zakat melalui lembaga resmi masih rendah.
Selain itu, integrasi penuh berpotensi memunculkan persoalan konstitusional terkait kesetaraan warga negara. Sebagai alternatif, optimalisasi mekanisme tax deduction dapat menjadi solusi transisional yang adil dan pragmatis. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada digitalisasi sistem, pengawasan terpadu, dan peningkatan literasi masyarakat agar zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen yang efektif untuk mengurangi beban ganda umat Islam sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan nasional.
Refleksi
Zakat memiliki potensi strategis untuk berperan sebagai instrumen fiskal yang mendukung terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Namun, realisasi potensi ini menuntut regulasi yang kokoh, tata kelola yang transparan, dan sinergi yang erat antara negara, BAZNAS, serta lembaga amil zakat lainnya.
Dalam kondisi saat ini, solusi yang paling realistis adalah harmonisasi antara pajak dan zakat melalui skema pengurang pajak (tax deduction) yang lebih efektif, disertai optimalisasi penghimpunan zakat dan distribusi yang produktif. Gagasan penggantian pajak dengan zakat sepenuhnya (tax substitution) masih menghadapi kendala serius, baik dari aspek penerimaan negara, keadilan fiskal, maupun kesiapan infrastruktur.
Refleksi ke depan mengarah pada perlunya integrasi sistem zakat dan pajak secara bertahap, dengan memperkuat literasi zakat, digitalisasi pengelolaan, serta pengawasan berbasis akuntabilitas. Apabila hal ini terwujud, zakat bukan hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur fiskal nasional yang berlandaskan nilai syariah dan prinsip keadilan, sehingga mampu berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat dan pembangunan bangsa.